Bab, Pasal 4 Point F:
Akses yang berkeadilan masih dipertanyakan sebab pada ketentuan di dalam RUU/UU BHP kewajiban BHP/Satuan pendidikan untuk menerima “mahasiswa pandai namun tidak mampu” hanya 20%, hal ini dapat dilihat pada dirumuskannya ketentuan dengan kata-kata “minimal 20%” (lihat Pasal 46 ayat (1) RUU/UU BHP) ini akan menjadi exit strategy bagi BHP untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa tidak mampu hanya pada angka 20% saja di sisi lain terdapat benturan kepentingan antara BHP dengan dengan calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat yang menurut ketentuan UU BHP harus ikut menanggung biaya pendidikan maksimal 30% (lihat Pasal 41 RUU/UU BHP) untuk dapat menarik sumber pendanaan dari calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat, hal ini akan menjadikan secara langsung maupun tidak langsung kemampuan ekonomi calon mahasiswa / siswa menjadi salah satu bahan seleksi bagi BHP/satuan pendidikan untuk menerima calon mahasiswa / siswa tersebut masuk menjadi peserta didik. Exit strategy inilah yang dapat menjadi alasan yang dimungkinkan menurut UU ini bagi BHP/ satuan pendidikan untuk mengelak dari tanggungjawab untuk menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f.
Sebagai contoh kasus di dalam penerimaan mahasiswa baru suatu Universitas pada formulir pendaftarannya tercantum kalusula “berapa besar jumlah sumbangan biaya pendidikan yang disanggupi oleh calon mahasiswa jika mereka lulus tes masuk/ diterima menjadi peserta didik?” (hal ini pernah ditemukan pada formulir UM UGM), hal ini jelas merupakan suatu deteksi awal dari pihak satuan pendidikan untuk mengenali bagaimanakah kemampuan ekonomi yang dimiliki calon mahasiswa bersangkutan, hal ini dapat disalahgunakan oleh BHP/satuan pendidikan untuk melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru berdasarkan kemampuan ekonomi sebab hasil (nilai) tes masuk tidak pernah diumumkan secara terbuka ( pengumuman hanya menyebut nama, nomor peserta, dan jurusan/ fakultas di mana ia diterima), di sisi lain kewajiban untuk menerima calon peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi hanya “minimal” 20% saja, lalu bagaimana jika jumlah calon peserta didik yang tidak mampu dan lolos tes seleksi masuk misalnya berjumlah 60% maka bagi BHP/satuan pendidikan tidak ada kewajiban untuk menerima semua 60% calon peserta didik yang lolos tes seleksi masuk tersebut.
Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena adanya pembatasan akses ke pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan
“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, utnuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”
serta pelanggaran atas hak konstitusional Warga Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI perubahan kedua yang menyatakan
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Bab III Pasal 11: Ini yang menunjukkan bahwa BHP berada atau setidaknya condong di ranah hukum privat
Bab IV, Pasal 18 Ayat 2: Di sini tidak ada unsur mahasiswanya
Ayat 3: Mereka dapat (tidak wajib) menetapkan unsur lain (mis. Mhsw) dengan Anggaran Dasar ktika mahasiswa ga ducantumin berarti ga ngelanggar UU, karna ga wajib
Pada rumusan Pasal 18 ayat (2) RUU/UU BHP menafikan keberadaan mahasiswa sebagai salah satu pemangku kepentingan “terpenting” (subjek pendidikan) dan “terbesar” karena keterwakilan unsur mahasiswa tidak diwajibkan sebab tidak tercantum di dalam uraian ketentuan Pasal tersebut sedangkan apabila dibandingkan dengan pengaturan di dalam PP No. 152 tahun 2002 tentang BHMN UI (lihat Pasal 12 ayat (1) keterwakilan unsur mahasiswa di dalam organ representasi diwajibkan dan dijamin, meskipun jumlahnya hanya 1 (satu) orang, jelas hal ini melemahkan posisi tawar mahasiswa mengingat mahasiswa adalah pemangku kepentingan terpenting dan terbesar.
Pengaturan mengenai keterwakilan mahasiswa hanya diatur dengan norma yang dirumuskan secara fakultatif dengan penggunaan kata “dapat” pada ketentuan ayat (3) selain itu kalimat yang mengatur mengenai keterwakilan mahasiswa hanya di dalam penjelasan ayat (4). Hal ini jelas memberikan jaminan hukum yang lemah terhadap keterwakilan mahasiswa di dalam organ representasi (mengenai pentingnya organ repersentasi lihat tugas, kewenangan dan fungsinya di Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 22 RUU/UU BHP).
Jika kita mengacu kepada asas demokrasi dan konsisten dalam penerapannya maka keterwakilan mahasiswa dalam organ representasi pemangku kepentingan adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi sehingga pengaturannya haruslah dirumuskan dengan norma yang imperatif bukan fakultatif. Sungguh sangat disayangkan jika ada anggota DPR RI yang menyatakan RUU/UU BHP ini adalah merupakan koreksi atas PP BHMN karena ternyata pengaturan RUU/UU BHP ini lebih buruk daripada PP BHMN, bahkan keterwakilan mahasiswa yang cuma 1 atau 2 orang di dalam PP BHMN itupun dirasa masih kurang adil dalam merepresentasikan kepentingan mahasiswa sebab jumlah anggota MWA (organ representasi di dalam BHMN) berjumlah antara 20-21 orang sehingga suara aspirasi mahasiswa seringkali kalah jika diadakan pengambilan keputusan melalui voting, kemudian yang terjadi adalah suatu kebijakan yang dapat merugikan kepentingan mahasiswa, ada juga kritik yang menyatakan keterwakilan unsur mahasiswa yang cuma 1 atau 2 orang itu hanyalah pelengkap derita dan sarana legitimasi dalam pengambilan kebijakan.
Hal ini merupakan pelanggaran (atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar) terhadap Hak Asasi Manusia karena tidak adanya jaminan hukum yang kuat atas representasi mahasiswa sebagai pemangku kepentingan terpenting (subjek pendidikan) dan terbesar di dalam organ representasi pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan
“Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”
serta pelanggaran atas hak konstitusional Warga Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI perubahan kedua yang menyatakan
“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Bab IV : Pasal 35 (C):
ketentuan ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena pengaturannya diserahkan kepada organ representasi pemangku kepentingan bukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard jika tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Bab V Pasal 37 (1):
Salah satu implikasinya adalah bahwa ketika BHP bankrupt maka kekayaan pendiri tidak terkena. Ketika bhp didirikan oleh pemerintah, maka ketika bhp bankrupt kekayaan Negara tidak bisa digunakan untuk menalanginya..
Perlu diingat kekayaan Negara awal pada BHPP dan BHPPD ini termasuk di dalam kategori kekayaan Negara yang dipisahkan sehingga menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal merupakan termasuk kategori keuangan Negara.
Pasal 37 (3): Perlu dikaji lebih lanjut apa implikasinya ketika yayasan menjadi BHP
Pasal 38 (1&2):
perlu diperjelas apakah ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2 ) ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan BHPP dan BHPPD akan masuk ke dalam ranah hukum privat ataukah publik karena dinyatakan sebagai bukan penerimaan Negara?, jika hal ini masuk di dalam ranah hukum privat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi privatisasi material (bukan privatisasi nilai) pada BHPP dan BHPPD (privatisasi sektor pendidikan) dengan alasan sebagai berikut:
- Dapat disimpulkan dari pendapat John D. Donahue bahwa “privatisasi sebagai pendelegasian kewajiban publik kepada organisasi swasta”, sebagaimana kita ketahui pendidikan adalah salah satu kewajiban Negara (lihat pembukaan UUD Negara RI tahun 1945) jadi pendidikan adalah kewajiban publik yang harus diberikan dalam bentuk pelayanan publik, di sisi lain BHPP dan BHPPD memiliki karakter yang sangat mirip dengan “organisasi swasta” karena menurut Pasal 38 ayat (1) dan (2) semua bentuk pendapatan dan sisa pendapatan tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak dengan kata lain bukan termasuk di dalam lingkup keuangan Negara (hal ini bertentangan dengan Pasal Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- Menurut Prof. Safri Nugraha yang menyimpulkan pendapat dari E.S. Savas “privatisasi diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan aset-asetnya”.
Menurut Prof. Safri Nugraha privatisasi memiliki resiko sebagai berikut:
1. Di berbagai negara, privatisasi justru menciptakan kenaikan harga dari public service yang disediakan kepada masyarakat.
2. Di banyak negara, privatisasi ditentang oleh serikat buruh karena sering menciptakan PHK massal di BUMN yang diprivatisasi. Hal ini disebabkan karena BUMN yang diprivatisasi harus efisien, dan ini berarti jumlah pekerja dalam BUMN tersebut harus dirasionalisasi.
3. Privatisasi sering diartikan sebagai pesan sponsor dari perusahaan-perusahaan transnasional (MNC) untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengambil alih BUMN-BUMN yang ada.
4. Seringkali BUMN yang diprivatisasi masih memiliki monopoli sehingga yang terjadi adalah pengalihan monopoli dari negara ke swasta.
5. Privatisasi sering diartikan sebagai komersialisasi public service karena di banyak negara, untuk menciptakan efisiensi di sektor public service, privatisasi mengenakan tarif atau biaya-biaya baru yang tidak dikenal pada saat public service tersebut dikelola oleh pemerintah.
Jadi tidaklah mengherankan akibat yang nyata dari privatisasi satuan pendidikan pemerintah adalah kenaikan biaya kuliah/sekolah karena hal tersebut adalah merupakan resiko dari adanya privatisasi.
Konsekuensi hukum lainnya jika hal ini dinyatakan masuk dalam ranah hukum privat adalah setiap ada penyalahgunaan keuangan BHPP dan BHPPD tidak dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi karena unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi melainkan bisa dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan.
Penjelasan Ayat (3)
Kewajiban penanaman kembali ke dalam badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk mencegah agar badan hukum pendidikan tidak melakukan kegiatan yang komersial.
Komersialisasi pendidikan tidak hanya terjadi dengan adanya pengalihan aset-aset satuan pendidikan pendidikan yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar menjadi aset-aset komersial sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan hasil dari unit-unit komersial yang dimiliki BHP, melainkan juga yang terpenting adalah adanya paradigma yang berubah di mana pelayanan pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sebuah kewajiban pelayanan publik (public service) oleh negara melainkan sudah menjadi suatu “komoditas” (private goods) yang dicirikan dengan adanya mekanisme pasar untuk menentukan harga dari pelayanan pendidikan sehingga “harga” dari pelayanan pendidikan yang harus dibayar peserta didik/masyarakat bisa menjadi fluktuatif bahkan bisa menjadi tidak terjangkau oleh semua kalangan seperti layaknya barang mewah, kondisi yang demikian akan mengeksploitasi peserta didik/masyarakat karena kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting untuk era seperti sekarang. Hal ini akan terjadi jika peran negara dalam pelayanan umum menjadi terpinggirkan/diminimalisir padahal negara kita adalah negara kesejahteraan bukan negara liberal yang menghendaki minimalisasi campur tangan negara dalam aspek-aspek penting kehidupan masyarakat.
Pasal 41 (1): di dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diketahui andanya 4 (empat) komponen pembiayaan pendidikan dasar, yaitu:
- biaya operasional
- biaya investasi
- beasiswa
- bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik
Pasal 41 ayat (2) ini dirumuskan dengan norma fakultatif sehingga bukan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.
Pada Pasal 41 ayat (3) terdapat degradasi komponen biaya yang ditanggung pemerintah dalam pembiayaan BHPP dan BHPPD di tingkat pendidikan menengah karena hanya ditanggung 3 (tiga) komponen saja, yaitu:
- biaya investasi
- beasiswa
- bantuan biaya pendidikan
sedangkan untuk komponen biaya operasional tidak ditanggung sepenuhnya.
Cermati bahwa pemberian dana didasarkan standar minimal. Jadi ketika sekolah itu menetapkan standar lebih, maka yang ditanggung tetap yang standar minimum
Pasal 41 Ayat 4: Pada Pasal 41 ayat (4) ini dapat kita ketahui adanya kewajiban minimal pemerintah dalam membiayai biaya operasional pendidikan menengah yaitu 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional saja, jadi besar kemungkinan BHPP dan BHPPD ataupun peserta didik dan masyarakatlah yang akan menanggung 2/3 (dua pertiga) biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum jika pemerintah hanya memberi 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. Artinya hal ini akan dapat memberatkan masyarakat.
Pada Pasal 41 ayat (4) ini hanya 3 komponen saja yang ditanggung oleh pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan tinggi, yaitu:
- biaya investasi
- beasiswa
- bantuan biaya pendidikan
sedangkan untuk komponen biaya operasional tidak ditanggung sepenuhnya.
Pada Pasal 41 ayat (4) ini dapat kita ketahui adanya kewajiban minimal pemerintah dalam membiayai biaya operasional pendidikan menengah yaitu 1/2 (setengah) dari biaya operasional saja, jadi besar kemungkinan BHPP dan BHPPD ataupun peserta didik dan masyarakatlah yang akan menanggung 1/2 (setangah) biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum jika pemerintah hanya memberi 1/2 (setengah) dari biaya operasional. Artinya hal ini akan dapat memberatkan masyarakat.
Pasal 41 ayat 7 & 8: Ini adalah Pasal yang memberikan “angin surga” bagi seluruh perserta didik di tingkat pendidikan menengah, apabila dikaitkan dengan ketentuan sanksi di dalam RUU/UU BHP (lihat Pasal 62) diatur ketentuan mengenai sanksi administrasi yang akan dijatuhkan apabila Pasal 41 ayat (8) ini dilanggar.
Pasal 41 Ayat 9: Ini adalah Pasal yang memberikan “angin surga” bagi seluruh perserta didik di tingkat pendidikan tinggi (mahasiswa), apabila dikaitkan dengan ketentuan sanksi di dalam RUU/UU BHP (lihat Pasal 60) maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan keputusan dan pencabutan izin yang akan dijatuhkan apabila Pasal 41 ayat (9) ini dilanggar, namun sanksi tersebut kewenangannya diserahkan ke kebijakan Menteri apakah akan dijatuhkan ataukah tidak. Artinya bagi PT BHPP masih bisa melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (9) apabila mendapat dispensasi dari Menteri. Pengaturan mengenai sanksi ini jelas tidak setegas pada Pasal 41 ayat (8) karena masih bisa memberikan celah bagi pihak yang ingin melanggar sehingga patut disayangkan. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih bisa dibebani tanggungan pendanaan pendidikan tinggi lebih dari 1/3 (sepertiga) biaya operasional jika terdapat dispensasi Menteri yang mengizinkan hal itu, padahal bisa jadi menanggung 1/3 (sepertiga) biaya operasional pendidikan saja sudah memberatkan.
Kata – kata “Bentuk Hibah” di ayat 10: Ini yang harus dicermati. Hibah di sini diartikan apa? Klo melihat hibahseperti yang dirumuskan dalam proyek IMHERE oleh World Bank, akan menyebabkan semua BHP menjadi kompetitif untuk mengajukan proposal yang paling sesuai dengan maunya pemerintah (baca: antek Worl Bank).
Pasal 41 (1) ”portofolio”: Artinya BHP bisa main saham. Satu lagi indikasi bahwa BHP ada di ranah hukum privat. Masalah investasi asing, itu disangkal oleh Irwan Prayitno. Tetapi ingat bahwa Perpres no 77 tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi yang mengatur pendidikan sebagai salah satu aset yang bisa ditanami modal (asing maksimal 49%) belum dicabut.
Pasal 42 ayat (1) ini adalah pasal yang menunjukkan adanya kebolehan pada komersialisasi aset PT BHPP
yang patut disayangkan dalam ketentuan Pasal 42 ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang diatur di dalam RUU/UU BHP apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang diaturnya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan adanya moral hazard, ketentuan mengenai sanksi hanya diatur di dalam Pasal 60 RUU/UU BHP dimana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pembatalan keputusan dan pembatalan izin satuan pendidikan, kemudian kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak sanksi tersebut ada di Menteri. Pihak PT BHPP dapat melanggar ketentuan Pasal 42 ini dan perbuatan tersebut tidak termasuk kategori melanggar peraturan perundang-undangan jika memperoleh dispensasi dari Menteri.
Pasal 43: Pasal 43 ini adalah pasal yang menunjukkan adanya kebolehan pada komersialisasi aset PT BHPP
Hal yang patut disayangkan dalam ketentuan Pasal 43 ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang diatur di dalam RUU/UU BHP apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang diaturnya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan adanya moral hazard, ketentuan mengenai sanksi hanya diatur di dalam Pasal 60 RUU/UU BHP dimana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pembatalan keputusan dan pembatalan izin satuan pendidikan, kemudian kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak sanksi tersebut ada di Menteri. Pihak PT BHPP dapat melanggar ketentuan Pasal 42 ini dan perbuatan tersebut tidak termasuk kategori melanggar peraturan perundang-undangan jika memperoleh dispensasi dari Menteri.
Pasal 44 ayat (3) menjadi bermasalah sebab dana hibah berarti bukan merupakan pengeluaran rutin pemerintah dalam APBN melainkan hanya bersifat bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan BHP. Apabila dilihat dari skala prioritas maka tidak dimasukannya dana pendidikan di dalam pengeluaran rutin kemudian hanya menjadi hibah maka telah terjadi degradasi skala prioritas dana pendidikan di dalam APBN.
Pasal 46: Pasal ini merupakan exit strategy bagi BHPP dan BHPPD sebagai sudah dijelaskan pada uraian di analisa Pasal 4 ayat (2) huruf f RUU/UUBHP untuk mengelak dari tanggungjawab untuk menerima calon peserta didik dengan potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi yang hanya menjadi kewajiban minimal bagi BHPP dan BHPPD sebanyak 20% saja dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru, sehingga BHPP dan BHPPD tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima calon peserta didik dengan potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi lebih dari 20% jumlah keseluruhan peserta didik yang baru, sedangkan di sisi lain terdapat tarik menarik kepentingan antara calon peserta didik dengan BHPP dan BHPPD (satuan penyelenggara pendidikan) untuk dapat menarik sumber pendanaan dari calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat, hal ini akan menjadikan secara langsung maupun tidak langsung kemampuan ekonomi calon mahasiswa / siswa (calon peserta didik) menjadi salah satu bahan seleksi bagi BHP/satuan pendidikan untuk menerima calon peserta didik tersebut masuk menjadi peserta didik. Jelas hal ini akan sangat berpengaruh pada terhambatnya aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan sehingga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara.
Pasal 46 ayat (2) dengan mewajibkan bagi BHP untuk memberi beasiswa minimal kepada 20% dari keseluruhan jumlah peserta didik jelas merupakan suatu hal yang tidak bijak, jika nanti ternyata jumlah siswa yang membutuhkan beasiswa lebih dari 20% kemudian BHP hanya mampu memberikan beasiswa bagi 20% peserta didik saja lalu kemudian siapakah yang akan menanggung biaya pendidikan kelebihan dari jumlah peserta didik yang membutuhkan biaya pendidikan (beasiswa) tadi? dalam RUU/UU hal ini tidak secara jelas diatur. Tidak ada sanksi yang tegas apabila BHP melanggar ketentuan Pasal ini.
Pasal 50 (1)Perlu diperjelas apakah laporan keuangan BHPP, BHPPD, BHPM baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah apakah meruapakan dokumen yang terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja ataukah dokumen yang bersifat rahasia.
Pasal 52 (2&3): Pasal 52 ayat (3) pembatasan kewenangan BPK dan Irjend untuk melaukan audit terhadap BHPP dan BHPPD sebatas hanya pada dana hibah saja menunjukan adanya suatu karakteristik yang menegaskan bahwa BHPP dan BHPPD adalah entitas hukum privat (swasta), hal ini akan dapat bertentangan dengan ketentuan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, meskipun RUU/UU BHP merupakan lex priori dari UU Keuangan Negara (lex postriori) akan tetapi hal ini dapat membuat kerancuan mengenai definisi keuangan Negara yang dianut di dalam UU Keuangan Negara.
Penjelasan Ayat (3)
Berhubung dana hibah berasal Angaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka otoritas pengawasan negara berhak untuk melakukan audit keuangan berlaku hanya pada bagian keuangan badan hukum pendidikan yang berasal dari hibah.
Pasal 55 ayat (2) harus diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pegawai badan hukum pendidikan karena statusnya bukan sebagai PNS melainkan hanya sebagai pekerja sehingga seharusnya tunduk kepada UU Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai pegawai badan hukum pendidikan ini pada BHPP dan BHPPD menunjukkan karakteristik yang menegaskan bahwa BHPP dan BHPPD adalah entitas hukum privat (swasta).
Di sini berlaku UU Ketenagakerjaan
Penjelasan Ayat (3)
Tenaga badan hukum pendidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan tetap harus membuat perjanjian dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, karena sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, yang bersangkutan belum diangkat oleh badan hukum pendidikan.
Di sini berlaku UU Ketenagakerjaan
Penjelasan Ayat (3)
Tenaga badan hukum pendidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan tetap harus membuat perjanjian dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, karena sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, yang bersangkutan belum diangkat oleh badan hukum pendidikan.
Pasal 56: Ketentuan Pasal 56 ini menunjukkan persamaan karakter BHP dengan perusahaan swasta layaknya Perseroan Terbatas.
Pasal 57 (B): kemungkinan terjadinya pailit muncul sebagai konsekuensi logis dari diperbolehkannya kegiatan dagang. Selain itu pailit juga dimungkinkan ketika BHP tidak mampu memenuhi pembiayaan
Apabila dicermati di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada ketentuan Pasal 2 tidak kita temukan mengenai syarat khusus bagi suatu BHP untuk bisa dipailitkan, seperti adanya izin dan pengajuan dari Pejabat berwenang untuk mempailitkan BHP sehingga untuk mempailitkan BHP cukup dengan syarat adanya dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas satu satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka BHP dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri, salah satu kreditornya dan kejaksaan demi kepentingan umum. Padahal BHP merupakan suatu lembaga yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat, sebagai contoh Perguruan Tinggi yang memiliki ribuan mahasiswa, seharusnya dalam hal mempailitkannya tidaklah mudah dan sederhana melainkan harus ada izin dan pengajuan dari Pejabat yang berwenang (prosedur yang lebih berat) demi melindungi kepentingan umum.
Pasal 63: ketentuan mengenai sanksi yang tegas ternyata tidak diberlakukan terhadap Pasal-pasal yang krusial seperti Pasal 41 ayat (9), Pasal 43, Pasal 46 ayat (2) sehingga Pasal-pasal krusial akan menjadi sulit untuk diberlakukan secara konsisten jika tidak dilekatkan sanksi.
Admin )(

Rabu, 11 Maret 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
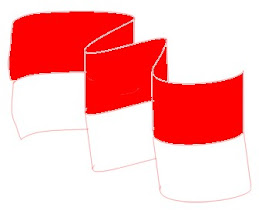











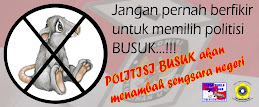

Tidak ada komentar:
Posting Komentar